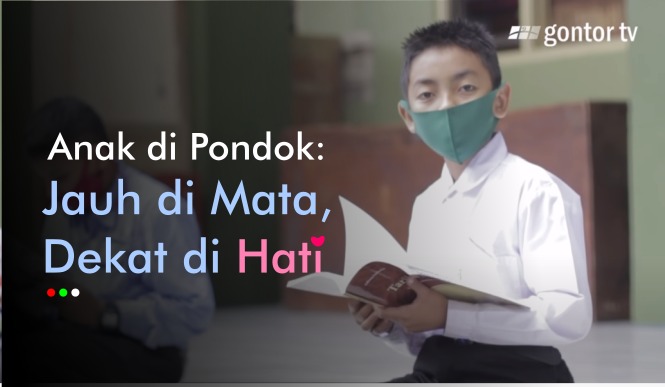Sebuah pepatah Arab mengatakan “zur ghibban, tazdad hubban”. Secara lepas, pepatah tadi mengatakan bahwa cinta akan bertambah dengan sedikitnya frekuensi pertemuan. Semakin sedikit sesuatu, semakin manis ia terasa.
Sebagai sebuah pepatah, tentunya ia merupakan kristalisasi dan akumulasi dari pengalaman dan fenomena yang dirasakan secara bersama-sama oleh tiap individu dalam sebuah kebudayaan atau bahkan peradaban.
Sebagai sebuah tesis, mungkin ia memiliki anti-tesis yang menjadi penyeimbang di sisi lain neracanya. Sebagaimana “jarrib wa laahidz takun aarifan” yang ‘berpasangan’ dengan “fakkir qabla an ta’zima”, zur ghibban mungkin punya jodohnya. Tapi hari ini kita sedang begitu tertarik dengan kata mutiara ini dan kebetulan penulis juga belum menemukan jodohnya yang benar-benar se-kufu. (Jika pembaca menemukan, bolehlah menuliskannya di kolom komentar)
Anak, tidak diragukan lagi, adalah permata hati bagi kedua orang tuanya. Senyumnya menentramkan hati, makannya yang lahap mengenyangkan perut, dan demamnya adalah demam orang tuanya. Saat anak kita yang berusia 5 tahun bisa menghafal Al-Fatihah, itu berita yang lebih penting daripada seorang anak kecil nun jauh di sana yang bisa menghafal seluruh surat dalam Al-Quran.
Sebagai permata, sebagian orang berpikir, tentu sangat indah jika ia dapat dilihat setiap hari. Namun bagaimana jika anak harus melangkah untuk masuk ke pondok, menuntut ilmu demi menjadi anak sholeh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya kelak?
Di sinilah pepatah zur ghibban tazdad hubban membuktikan bahwa dirinya benar. Tempaan abad memang tidak bisa ditepis; kata-kata singkat itu tidak bisa disangkal; anak yang masuk pondok memang kini berada jauh di mata, semakin jarang dilihat, namun… ia semakin dekat di hati, semakin sering tersebut dalam bulir doa.
Beberapa bulan ini, pepatah itu kian mendapat pembenaran secara kolektif. Karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan saat ini, anak-anak usia sekolah kini banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di sekolah. Mereka memiliki intesitas pertemuan yang lebih tinggi dengan orang tuanya dibanding sebelumnya. Apakah grafik cinta orang tua kepada anaknya memiliki korelasi positif dengan bertambahnya jam pertemuan itu?
Saya rasa masing-masing kita sudah menjadi peneliti yang cukup mumpuni untuk menjawab pertanyaan itu. Mungkin regresi linear tidak dibutuhkan untuk mencari jawaban itu.
Sebagai sebuah pepatah, tentu zur ghibban tazdad hubban adalah sebuah generalisasi. Dan sebagai sebuah generalisasi, tentu ia memiliki pengecualian. Sebagai sebuah objek penelitian, tentu ada saja outlier yang memiliki karakteristik yang berbeda dari normal distribution. Tentu ada individu yang merepresentasikan fenomena black swan dari pepatah itu.
Tapi sebagai sebuah kata bijak; ia terlalu indah untuk diributkan dengan berbagai kompleksitas itu. Kata bijak adalah mutiara; ia tersimpan dalam cangkang waktu, berkembang sedikit demi sedikit, menunggu untuk ditemukan dan dikenakan dikenakan untuk menyempurnakan keindahan paras yang mengenakannya.
Mari sekarang kita lihat dari sudut pandang seorang anak. Manakah yang lebih ia rindukan, orang tua yang ia temui setiap jam, atau yang ia temui dalam sekali putaran bumi mengelilingi matahari?
Sekali lagi, mungkin kita tidak perlu memerlukan komputer dengan kemampuan komputasi super untuk menjawab soal itu.
Anak yang berada di pondok… jarang dikunjungi, atau bahkan tidak boleh dikunjungi, sebenarnya sedang menyusun sebuah istana cinta kepada orang tuanya. Setiap hari ia meletakkan satu bata. Setiap hari ia menguatkan bangunan itu.
Suatu hari… di hari yang indah itu, ia datang, insyaAllah dan mengecup punggung tangan orang tuanya. Dalam hatinya berguman. Terima kasih telah mendoakanku selama berada di pondok. Terima kasih atas kiriman cintanya yang tak pernah putus.
Gontor, 10 Agustus 2020
M. Taufiq Affandi, Guru KMI Gontor dan Dosen Universitas Darussalam Gontor.
Editor & Reviewer:
Dr. Abdul Hafidz Zaid, Lc., M.A.
Dr. Adib Fuadi Nuriz, M.A.
M. Faqih Nidzom, M.Ag.